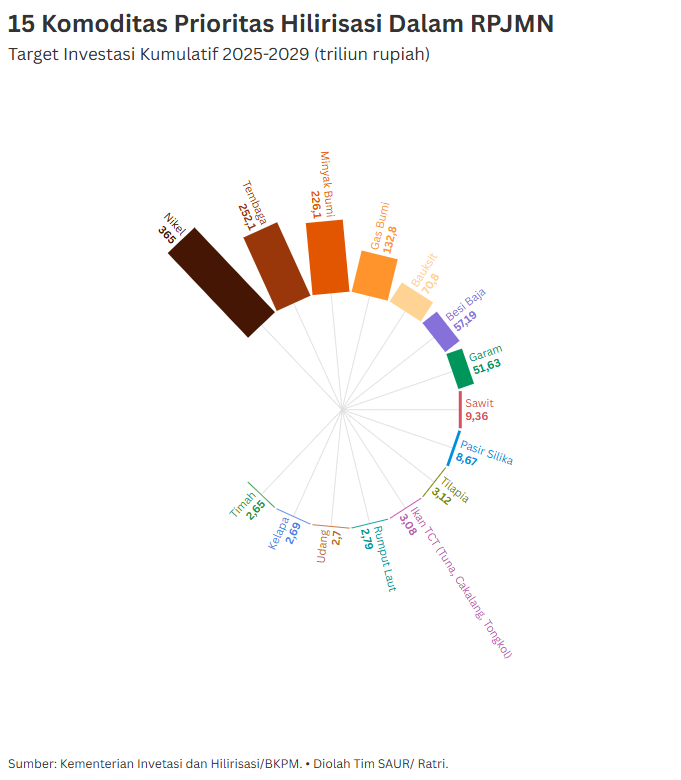Puluhan pesan masuk, baik lewat WhatsApp maupun disampaikan langsung kepada Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Isinya berulang, datang dari penjuru Indonesia: keluhan soal kepastian hukum.
“Keluhan soal isu ketidakpastian hukum ini memang cukup konsisten kami terima dari para pelaku usaha,” ujar Shinta kepada Suar melalui keterangan tertulis (31/07).
Dari izin mendirikan bangunan, dokumen AMDAL, hingga ketidaksinkronan aturan pusat dan daerah. Meski sektor usaha, skala bisnis, dan wilayahnya berbeda-beda, pola keluhannya tetap sama: proses perizinan dan kebijakan yang serba tak terduga, yang tak hanya memperlambat, tapi juga mengganggu iklim usaha.
Pada Juni lalu, Apindo menggelar survei terhadap lebih dari 100 perusahaan di 18 provinsi. Hasilnya mengonfirmasi kegelisahan itu: 72% responden merasa dokumen persyaratan terlalu banyak, 65% mengaku terpaksa memakai jasa pihak ketiga, yang justru memperumit sekaligus menambah biaya, dan 54% menyoroti lamanya proses rekomendasi, kendala teknis di sistem OSS, serta ketidakcocokan aturan pusat dan daerah.
“Untuk dokumen AMDAL saja, mayoritas perusahaan bisa habiskan waktu lebih dari setahun. Padahal ini hanya tahap awal,” ungkap Shinta. Keluhan yang dulu muncul sporadis, kini telah menjadi pola masalah yang sistemik.

Lebih dari Sekadar Tumpukan Dokumen
Bagi dunia usaha, ketidakpastian bukan sekadar urusan dokumen. Ia berarti biaya tersembunyi: terhentinya rencana ekspansi, relokasi ke luar negeri, atau naiknya harga produk karena proses panjang dan biaya tambahan.
“Bisnis selalu tumbuh di atas perhitungan risiko. Tapi kalau aturannya sendiri tidak konsisten, susah sekali untuk merencanakan,” tegas Shinta.
Sejumlah upaya reformasi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah. Revisi PP 5/2021 menjadi PP 28/2025 memperkuat sistem OSS-RBA, penerapan service level agreement (SLA) untuk batas waktu layanan, hingga prinsip fiktif positif: jika permohonan izin tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu, dianggap otomatis sah. Namun, semangat reformasi di pusat seringkali masih terhalang oleh realitas di lapangan.
“Permen atau peraturan daerah harus disesuaikan juga. Kalau hanya kebijakan utamanya bagus, tapi turunannya tidak sinkron, masalahnya tetap ada,” ujar Shinta.
Karena itulah, Apindo mendorong agar pemerintah tak hanya fokus pada reformasi prosedural, tetapi juga mengevaluasi dampak kebijakan baru bagi dunia usaha melalui regulatory impact assessment (RIA), serta mengurangi tumpukan aturan yang malah saling bertabrakan, fenomena yang kerap disebut regulatory overload.
Pandangan dari Singapura: Konsistensi yang Jadi Nilai Jual
Bagi Suryopratomo, Duta Besar RI untuk Singapura, keberhasilan negeri tetangga ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan hasil budaya regulasi yang konsisten dan dapat diprediksi. “Pemerintah Singapura jarang sekali membuat perubahan kebijakan yang mendadak,” ujar Suryopratomo kepada Suar (30/07).
Setiap revisi kebijakan yang bersifat strategis selalu diawali proses konsultasi publik, regulatory impact assessment, hingga perencanaan multi-tahun. “Itu memberi ruang bagi pelaku usaha, baik lokal maupun asing, untuk beradaptasi dan menyusun strategi bisnis mereka,” tambahnya.
Selain kepastian kebijakan, ada satu prinsip penting yang dijunjung tinggi: regulatory simplicity. Proses perizinan sebagian besar dilakukan digital, memakai sistem single window seperti BizFile dan GoBusiness.
“Bahkan untuk investor asing, pendirian perusahaan bisa selesai hanya dalam hitungan jam,” kata Suryopratomo.
Semua dokumen hukum, aturan, dan insentif pun tersedia transparan, dalam bahasa Inggris, sehingga dapat langsung diakses oleh calon investor. “Prinsip dasarnya adalah: jangan membuat regulasi yang tidak perlu,” jelasnya. Singapura lebih memilih tak mengatur hal-hal yang tak penting ketimbang membuat aturan yang akhirnya justru mempersulit.
Di luar regulasi, ada pula faktor pendukung yang tak kalah penting. Stabilitas politik dan hukum, birokrasi yang minim interpretasi ganda, hingga rule of law yang ditegakkan ketat. Belum lagi, sistem perpajakan yang kompetitif, sumber daya manusia terampil, serta kemudahan adopsi teknologi dan reformasi kelembagaan.
“Ekosistem bisnis Singapura terhubung erat ke pusat-pusat ekonomi dunia. Itu juga memberi daya tarik lebih,” kata Suryopratomo. Hal ini membuat Singapura menjadi benchmark regional dalam kemudahan berusaha—bukan karena aturannya selalu ringan, tetapi karena prosesnya dibuat transparan, konsisten, dan adil.
Suryopratomo mengakui, bukan berarti Indonesia harus menyalin mentah-mentah model Singapura. “Setiap negara punya konteks dan kebutuhan sendiri,” katanya.
Namun prinsip-prinsip dasar seperti konsistensi regulasi, keterbukaan informasi, dan evaluasi kebijakan berbasis dampak tetap relevan. “Indonesia sudah melakukan banyak kemajuan, seperti digitalisasi layanan OSS, reformasi struktural, dan peninjauan ulang aturan,” ujar Suryopratomo. “Tapi perjalanan ini tetap butuh konsistensi dan keterlibatan lintas pihak: pemerintah pusat, daerah, dan tentu saja pelaku usaha.”
Pelajaran paling penting, kata Suryopratomo, adalah bahwa kepastian hukum bukan hanya soal kecepatan atau jumlah dokumen, melainkan soal kepastian proses yang jelas, ruang adaptasi bagi pelaku usaha, dan keberanian pemerintah menghapus regulasi yang tidak perlu.
“Karena pada akhirnya, kepercayaan pelaku usaha tumbuh bukan dari janji, tapi dari konsistensi kebijakan di lapangan,” pungkasnya.
Memetakan Masalah, Menawarkan Solusi
Dalam waktu dekat, Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) Apindo akan menjadi ajang penting untuk membahas masalah ini. Forum tahunan tersebut mempertemukan pelaku usaha dari skala UMKM hingga perusahaan besar, dengan pemerintah dan ekonom. Tujuannya bukan hanya mendengar keluhan, tapi juga memetakan solusi strategis.
Mempertemukan pelaku usaha dengan pakar dan pemangku kebijakan seperti Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, dan Menteri Ekraf akan menjadi agenda utama. “Nantinya, akan ada Rekomendasi Strategis, poin-poin masukan dari dunia usaha untuk pemerintah demi perbaikan ekosistem investasi,” kata Shinta.
Apindo berharap, pembahasan kepastian hukum tak hanya fokus pada prosedur perizinan, tetapi juga menyentuh substansi kebijakan, termasuk konsistensi penerapan antara pusat dan daerah. “Kepastian hukum bukan soal satu izin cepat terbit, tapi bagaimana semua prosesnya transparan, jelas, dan bisa diprediksi,” tambahnya.
Indonesia punya potensi pasar besar, demografi produktif, dan transformasi digital yang sedang berjalan. Namun semua itu membutuhkan fondasi: kepastian regulasi. “Kepastian hukum adalah fondasi. Tanpa itu, sehebat apa pun potensi kita, selalu akan ada risiko usaha yang tak terukur,” tutup Shinta.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani memahami pentingnya kepastian hukum dan regulasi untuk menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan tiga langkah agar geliat investasi asing tetap berjalan prima di Tanah Air.
Langkah pertama yang dilakukan pemerintah melakukan pembenahan regulasi agar memberikan kepastian bagi investor. Dalam hal ini pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sedang langkah kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya sumber daya manusia Indonesia bisa memiliki daya tarik lebih tinggi terhadap investasi. Sebab, investor selalu mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia saat memulai investasi di suatu negara.
Ketiga, meningkatkan interaksi antara pemerintah dan investor. Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu mengadakan pertemuan dengan investor asing di sela-sela kunjungan ke luar negeri. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja Danantara Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investor asing ke Indonesia.