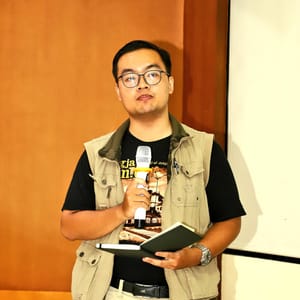Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa bakal kembali semarak dengan tambak-tambak ikan yang produktif. Tambak rakyat yang selama ini terbengkelai akan direvitalisasi guna mendorong kembali perekonomian masyarakat di kawasan pesisir.
Yang menarik, bila sebelumnya tambak-tambak itu diisi bibit udang dan bandeng, kini para petambak punya produk unggulan baru: ikan tilapia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, program revitalisasi ini mencapai 78.550 hektare tambak di Pantai Utara Jawa. Tujuannya, meningkatkan produktivitas perikanan budidaya nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menyatakan, tahap pertama akan diawali dengan revitalisasi 20.413,25 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat. Yakni, Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang.
Revitalisasi tambak tahap pertama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, 25 Agustus 2025 lalu.
Secara rinci, dari 20.413,25 hektare area revitalisasi tahap pertama, seluas 8.188,49 hektare area tambak terletak di empat kecamatan di Bekasi; 6.979,51 hektare tambak berada di lima kecamatan di Karawang; 2.369,76 hektare tambak berada di empat kecamatan di Subang; dan 2.875.48 hektare tambak berada di lima kecamatan di Indramayu.
Menurut Haeru, dengan pengelolaan modern, berbasis industri, dan menerapkan budidaya berkelanjutan, produktivitas tambak yang saat ini hanya 1 ton–2 ton per tahun dapat meningkat. "Komoditas yang dipilih adalah tilapia atau ikan nila salin," ujar Haeru dalam keterangan tertulis di situs KKP.
Menurut Haeru, ikan tilapia dipilih sebagai komoditas budidaya masif karena memiliki toleransi tinggi terhadap air payau, cepat tumbuh, dan teknik budidaya relatif mudah dikuasai. Selain itu, pasar domestik dan ekspor tilapia juga sangat terbuka – meski negara tujuan potensial masih perlu dikaji kembali lantaran tren pasar yang berubah-ubah.
Ikan tilapia dipilih sebagai komoditas budidaya masif karena memiliki toleransi tinggi terhadap air payau, cepat tumbuh, dan teknik budidaya relatif mudah dikuasai.
Lewat program revitalisasi ini, KKP menargetkan peningkatan produktivitas tambak budidaya menjadi 144 ton per hektare per tahun. Adapun saat ini cuma 0,6 ton per hektare per tahun.
"Volume produksi kami perkirakan akan mencapai 1,18 juta ton dengan nilai produksi Rp 30,65 triliun, serta menciptakan lapangan kerja bagi 119.100 masyarakat di sektor hulu maupun hilir," ungkapnya.
Volume produsi tersebut ditargetkan dapat tercapai dengan mengandalkan ikan tilapia premium berstandar ekspor, dengan ukuran panen 1 kg per ekor.
Kelak, dengan peningkatan produktivitas ini, Indonesia diharapkan dapat ikut memenuhi permintaan pasar blue food yang meningkat signifikan dari US$ 270 miliar pada 2020 menjadi US$ 420 miliar dolar pada tahun 2030 mendatang.
Pelajari kondisi
Menurut Sunaji, Kepala Desa Ambulu di Kecamatan Losari Cirebon, selain tingkat produktivitas yang meningkat, pemerintah perlu memperhatikan aspirasi, kesiapan masyarakat, dan faktor-faktor lain sebelum budidaya dimulai.
Pasalnya, tidak semua tambak di pesisir Pantura memiliki lanskap yang cocok untuk budidaya tilapia dalam skala masif sebagaimana dicanangkan pemerintah.
Toh, Sunaji bilang, meski Cirebon tidak termasuk dalam program tahap pertama, tahap lanjutan revitalisasi ini sangat dinantikan karena memiliki potensi besar.
Sejak lama, Desa Ambulu dikenal sebagai produsen bandeng dan udang terkemuka, dengan jenama "Bandeng Losari" yang terkenal di pasar perikanan budidaya. Namun, produktivitas tambak rakyat Ambulu berkurang karena banjir rob kerap melanda tambak-tambak tersebut.
"Kami menggunakan Dana Desa yang sangat terbatas untuk membuat tanggul sepanjang 1,2 kilometer karena belum ada kepastian dari Kementerian PU. Sesudah tanggul dibuat, kualitas air yang turun karena banjir rob membuat kami merombak tambak bandeng dan udang menjadi tambak garam yang lebih menguntungkan," ujar Sunaji saat dihubungi SUAR, Selasa (23/9/2025).

Dengan segala keterbatasan itu, Sunaji berkomitmen memaksimalkan peluang 800 hektare–900 hektare tambak di desanya untuk mendatangkan investor yang bersedia menanamkan modal di tambak garam rakyat yang sedang berjalan.
Sunaji tidak menyangkal kekhawatiran perubahan iklim berpotensi membuat desa pesisir terancam hilang. Namun, dia menyebut penduduk desanya tidak terlalu tertarik dengan wacana tersebut dan memilih bergerak dari yang ada.
"Program ketahanan pangan pemerintah membuat kami mempunyai semangat baru, termasuk mengeluarkan dana sendiri untuk memperbaiki tanggul dan membangun kembali tambak. Komoditas memang berubah ke garam, bukan karena tidak menghargai bandeng, tetapi garam lebih menguntungkan," jelasnya.
Pekan ini, Sunaji mengagendakan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta memfinalisasi profiling tambak dengan bantuan tim teknis dari IPB dan Universitas Bakrie. Lewat profiling tersebut, dia mengharapkan investor menjadi lebih yakin untuk menggerakkan produksi garam di Desa Ambulu.
"Sesudah kami bendung sendiri, pengusaha atau pemerintah mau apakan tambak ini silakan. Yang penting produktif dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya.
Tidak harus tilapia
Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi lanskap tambak rakyat di setiap daerah agar lebih akurat dalam memetakan tambak yang akan direvitalisasi. Risiko kerugian akibat pemaksaan budidaya secara masif tanpa pengkajian mendalam juga perlu dimitigasi.
Anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri mengingatkan, proyeksi kegagalan dari fase pertama seluas 20.000 hektare tambak tersebut sama besarnya dengan proyeksi keuntungan yang diimpikan pemerintah. Adapun potensi kegagalan itu dapat terjadi dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.
Secara ekologis, Rokhmin menggarisbawahi budidaya ikan satu spesies dalam skala raksasa berisiko menimbulkan ledakan wabah penyakit seperti pernah terjadi pada budidaya udang windu (Penaeus monodon) di Pantura, pesisir Sulawesi Selatan, dan pesisir timur Aceh pada 1985–1993. Begitu pula dengan budidaya udang vaname skala raksasa di Lampung.
Rokhmin menilai, sebenarnya di sepanjang Pantura masih ada beberapa spesies budidaya yang cocok. Seperti, bandeng, kepiting bakau, kepiting soka, ikan kerapu lumpur, selain udang windu dan udang vaname. "Teknik budidaya pun dapat memilih monokultur, polikultur, maupun silvo-fishery dengan hutan mangrove," ujar Rokhmin saat dihubungi SUAR, Selasa (23/9).
Sementara itu, dari sisi pasar, budidaya tilapia secara masif dapat menciptakan oversuplai pada saat terjadinya panen, baik di pasar domestik maupun ekspor. Ini karena selera dan preferensi konsumen belum sepenuhnya teruji menyukai tilapia asal Indonesia. Volume serapan domestik maupun ekspor juga terbatas.
Maka, Rokhmin mengingatkan, jangan seluruh tambak Pantura yang akan direvitalisasi itu menjadi pusat budidaya tilapia. "Harus disertai dengan beberapa spesies lain yang cocok. Mungkin nila salin cukup 10.000 hektare saja. Di samping itu, perlu diadakan sosialisasi dan promosi untuk menemukan pasar tilapia di dalam negeri maupun di luar negeri," jelasnya.